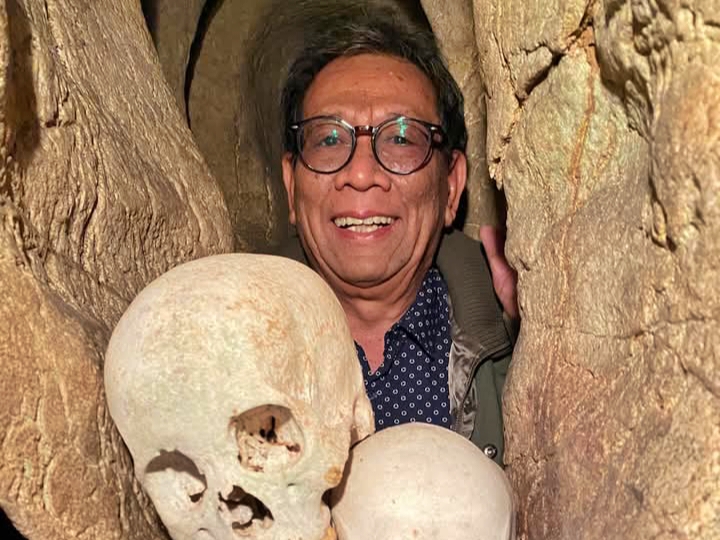Oleh: Wahjudi Djaja*
Lebih dari sebuah kota, Yogyakarta adalah rahim peradaban. Di dalamnya menyala energi serupa tirta ayudya yang memberikan kehidupan bagi siapapun yang meminumnya. Darinya lahir orang-orang yang tiada lelah mengukir sejarah di bidang kehidupan yang digelutinya.
Berdiri 7 Oktober 1756 kota ini tak pernah berhenti apalagi mati untuk selalu menginspirasi dan menghidupi. Ia menjadi saksi tidak saja detak kehidupan semua kalangan, tetapi juga bagi jatuh bangunnya Indonesia. Yogyakarta adalah ladang kehidupan dengan perisai yang amat kuat yang dibuka oleh Pangeran Mangkubumi.
Kota ini hadir dalam karakter budayanya. Berakar pada tradisi sejarah Mataram, mengalami transformasi masa kesultanan, dan menampilkan watak satriya pada era kemerdekaan. Ia merepresentasikan nilai-nilai keutamaan. Konsentrasi saat berkarya, semangat jiwanya membara, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dan tanggung jawab atas amanat yang disandang.
Pola hubungan manusia yang ada di dalamnya diatur dalam beragam falsafah. Kata-kata yang kemudian memprasasti dan menempel pada tiap denyut jantung warganya. Dua sisi eksistensial kemanusiaan yang menekankan hubungan erat antara rakyat dan raja serta antara umat dengan Tuhan tersimpan dalam sasanti golong gilig manunggaking kawula Gusti. Sementara tanggung jawab menjaga keseimbangan alam menjadi orientasi prinsip hamamayu hayuning bawana.
Tidak saja mendasarkan keberadaan kota dengan pertimbangan falsafah Jawa yang kuat, Sri Sultan Hamengku Buwono I juga merancangnya berdasar arsitektur dengan sentuhan yang matang. Bisa dilacak bagaimana jejak arsitektur peninggalan sejarahnya. Ruh budayanya dihidupkan dengan menciptakan tarian seperti Beksan Lawung dan Tarian Wayang Wong. Sampai Sri Sultan Hamengku Buwana X, kraton menjadi pusat kebudayaan yang menjadi penerus tradisi Mataraman.
Catatan penting perlu disampaikan terkait Sri Sultan Hamengku Buwana IX. Selain mematrikan tahtanya untuk kepentingan rakyat, peran beliau demi tegaknya NKRI tak bisa dilupakan. Saat Indonesia masih belia dan tertatih-tatih menapaki jalan sejarah, Ngarsa Dalem IX berani pasang badan menjaga kedaulatan. Empat tahun Yogyakarta menjadi ibukota dan selama itu pula keuangan negara di-back up oleh Sinuwun. Rakyat berdiri sebagai pagar betis bagi kelangsungan negara. Tak aneh, jika Bung Karno sampai berpesan, “Yogyakarta menjadi termasyhur oleh karena jiwa merdekanya. Hidupkanlah terus jiwa kemerdekaan itu”.
Saat zaman bergerak, kebudayaan tumbuh subur di Yogyakarta. Tercatatlah nama WS Rendra, Umbu Landu Paranggi, dan berderet sastrawan yang tiada lelah menggali laku budaya dan menata kata menjadi prasasti yang amat bermakna. Bacalah sajak Balada Orang-orang Tercinta (Rendra, 1957) atau Nyanyian Orang Urakan (Rendra, 1985). Dengan Bengkel Teater, Rendra berhasil membuat postulat yang sampai kini bisa kita resapi, “Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata”.
Affandi dan berpuluh pelukis menorehkan guratan jiwanya di lembar-lembar kanvas yang sampai kini melegenda. Azwar An dan beratus seniman pun tak pernah berhenti mengeskpresikan kata menjadi laku drama dan teater. Sawung Jabo dengan Sirkus Barock-nya bersama para musisi tak pernah kehilangan inspirasi saat bicara Yogyakarta. Dan kalangan kampus, menjadikan kota ini sebagai oase dimana kerinduan meledak setelah mereka wisuda. Koran Kedaulatan Rakyat menjadi saksi atas gegap gempita revolusi kemerdekaan sampai era pembangunan.
Di Yogyakarta, kata-kata menjadi hidup dan menginspirasi. Dan Yogyakarta adalah kota yang tak pernah kehilangan kata.
Dirgahayu Yogyakarta
Ksatrian Sendaren, 7 Oktober 2024
*Ketua Umum Keluarga Alumni Sejarah Universitas Gadjah Mada (Kasagama), Dosen STIE Pariwisata API Yogyakarta, Peraih Anugerah Kebudayaan Sleman 2023 Kategori Budayawan