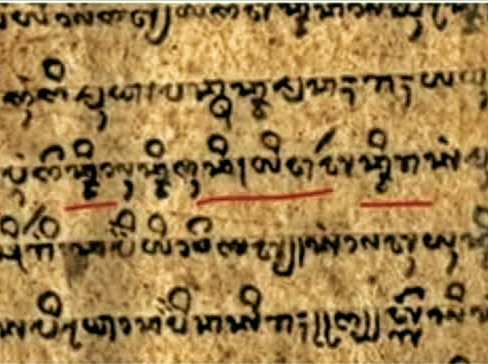Oleh: Wahjudi Djaja*
Minggu (7/4/2024) diminta menjadi narasumber dalam acara Indonesia Menyapa Siang RRI Pro3 Jakarta. Tema yang diangkat, “Makna Mendalam di Balik Tradisi Tradisi”. Mudik menjadi fenomena kultural yang khas Indonesia dan telah berakar jauh dalam sejarah bangsa. Menarik untuk melihat makna yang ada di dalamnya, baik yang dialami pemudik maupun masyarakat.
Lebih dari sekedar perpindahan manusia pada aspek geografis, dari kota ke udik (kampung), mudik adalah perjalanan mental spiritual. Bermula dari perantauan atau dalam konteks Jawa disebut boro, kota tetap merupakan medan kehidupan yang menawarkan beragam hal. Mulai lapangan kerja, pendidikan, sampai beragam kesempatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan. Migrasi merupakan keniscayaan mengingat desa atau kampung tak banyak menyediakan kebutuhan hidup. Karena orientasinya adalah mencari penghidupan, atau dalam istilah Jawa pangupo jiwo, maka perantau atau migran dipaksa keadaan untuk bisa menabung, hemat dan prihatin. Tidak logis jika mereka hidup foya-foya di kota, karena kelak harus “mempertanggung jawabkan” perantauannya saat pulang kampung dan bertemu sanak saudara.
Setahun lamanya mereka merantau, menapaki dinamika hidup yang keras. Ungkapan yang sering muncul, “kepala untuk kaki, kaki untuk kepala”. Dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, hidup didedikasikan untuk mencari nafkah, mengumpulkan rezeki dan membuka peluang hidup. Makan dengan garam adalah wajar dan biasa mengingat banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi.
Bisa jadi mereka mengalami transformasi, dari manusia udik yang ramah penuh kesabaran dan kearifan menjadi manusia kota yang keras dan pantang menyerah. Mereka akan sangat memahami ungkapan mencari “uang haram saja susahnya minta ampun apalagi yang halal”. Tentu, tak semua perantau mengalami perubahan mental karakter. Ada yang tetap menjaga irama pedesaan saat hidup di perkotaan, tetapi itu persentasenya kecil. Rata-rata, mereka sangat menghargai waktu, itungan, disiplin, dan tahan lapar. Mereka menjadi sangat paham susahnya mencari uang.
Maka momentum lebaran dengan mudik adalah saat dimana anak memberikan laporan kepada orang tua, anak dan istri atau suami. Terbayang, beberapa tetangga di Bayat (Klaten) pulang mudik dengan membawa mobil lengkap dengan oleh-oleh dari kota. Sedang yang berperan menjadi pedagang kecil di kota, saat mudik akan mampir pasar untuk membeli gula pasir, teh, roti dan tembakau untuk orang tua. Biasanya barang-barang itu dimasukkan dalam kardus lalu dipundak saat turun dari bis menuju rumah.
Namun ada pengalaman spiritual yang penting dicatat saat mereka mudik. Mereka kembali ke udik, tempat lahir dan dibesarkan. Mereka sesungguhnya secara simbolis kembali ke rahim, tempat indah penuh kedamaian dan ketenangan. Mereka merasa perlu untuk me-refresh kebatinan dengan ziarah ke makam leluhur dan keluarga, mengingat proses sejarah dan menyadari beragam kesalahan yang dilakukan selama hidup di kota. Mudik adalah momentun penyadaran tentang hakikat hidup.
Sampai di titik itu, mudik masih menjadi tradisi asali yang menyimpan beragam kearifan. Mulai berubah saat ukuran-ukuran dan etika moralitas ditinggalkan. Mudik dan segala turunannya–reuni, syawalan, wisata, kumpulan trah dan ujung (minta maaf kepada sanak saudara)–berubah menjadi etalage tempat segala yang gemerlap ditaruh dan ditempelkan agar bisa dilihat orang banyak. Pamer dan ujub tak bisa dihindari, hingga kohesi sosial–yang mestinya merapat mendekat saat lebaran–menjadi renggang dan menjauh. Untuk menghadiri kenduri atau syawalan ke saudara yang jaraknya tak jauh tak sungkan bawa mobil atau motor dan pantang jalan kaki.
Ruang yang terbuka bagi jiwa untuk kembali ke rahim (kasih sayang) semakin terkontaminasi oleh tradisi yang tak lazim. Apalagi narasi yang dibawa dan diceritakan menjadi “kota minded”. Momen syawalan lebaran yang mestinya riuh rendah dengan berbagi kisah menjadi kaku dan kering karena masing-masing asyik dengan androit model terbaru atau narasi yang didominasi sudut pandang kota. Kalau sudah begini, mudik tak ubah invasi budaya kota atas harmoni desa. Celakanya, agen perubahannya adalah manusia setengah kota setengah desa, kakinya di desa kepalanya di kota. Oalah…
Ksatrian Sendaren, 8 April.2024
*Budayawan Sleman, Ketua Umum Keluarga Alumni Sejarah Universitas Gadjah Mada (Kasagama)